Penerbitan buku-buku yang mendukung perjuangan pembebasan di Indonesia punya sejarah yang panjang. Sejak akhir abad ke-19, terutama di Jawa, tumbuh penerbit dan percetakan milik orang Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa yang menerbitkan sekitar 3.000 judul buku, pamflet dan terbitan lainnya sebelum kemerdekaan. Beberapa orang bumiputra yang magang di penerbitan ini kemudian tumbuh menjadi jurnalis dan penerbit sekaligus, seperti RM Tirtoadhisoerjo dan Mas Marco Kartodikromo yang sekarang dikenal melalui bukunya, Student Hidjo.
Mas Marco Kartodikromo dan istri | foto: KITLV
Pada 1906 pemerintah kolonial mengubah peraturan mengenai sensor. Sebelumnya setiap penerbit diharuskan menyerahkan naskah kepada penguasa sebelum dicetak, sehingga bisa disunting, diubah atau bahkan dilarang sebelum beredar. Namun peraturan yang baru menetapkan sensor represif, yakni pembatasan terhadap barang cetakan setelah diedarkan oleh penerbitnya. Dalam waktu singkat berdiri sejumlah penerbit bumiputra, yang menerbitkan suratkabar, majalah dan buku serta pamflet. RM Tirtoadhisoerjo kemudian menjadi penulis, penerbit dan redaktur suratkabar Medan Prijaji, yang tidak segan-segan mengkritik tatanan kolonial secara terbuka. Kalangan terpelajar memanfaatkan kebebasan dengan mengeluarkan terbitannya masing-masing, dengan tiras berkisar antara lima ratus sampai seribu eksemplar.
Produksi bacaan semakin marak ketika para penerbit bersinggungan dengan dunia pergerakan yang juga sedang tumbuh. Bukan hanya organisasi pemuda seperti Boedi Oetomo yang mulai menerbitkan pikiran mereka, tapi juga serikat-serikat buruh, anak-cabang organisasi rakyat seperti Sarekat Islam, perhimpunan ulama dan kaum perempuan. Suratkabar memang bentuk yang paling populer, tapi banyak juga karya-karya sastra dalam bentuk buku dan pamflet yang diedarkan. Bentuk terakhir biasanya dipilih oleh penerbit kecil karena disamping biaya produksinya lebih murah, harga jualnya juga bisa dijangkau oleh rakyat kebanyakan yang menjadi sasaran buku-buku semacam ini.
Di dalam pergaulan antara penerbit dan pergerakan inilah muncul buku-buku yang isinya mengecam kekuasaan kolonial dan sistem kapitalisme yang menjadi landasannya. Di kalangan pergerakan sendiri tumbuh kesadaran bahwa rakyat bumiputra yang menginginkan kebebasan harus memproduksi sendiri bacaannya, karena sudah terlalu lama dijajah pikirannya oleh penguasa kolonial. Pada 1919 Semaoen yang menulis Hikajat Kadiroen mencetuskan konsep 'literatuur socialistisch' (bacaan sosialis). Ia sendiri menulis Penoentoen Kaoem Boeroeh, semacam buku pegangan untuk aktivis serikat buruh di zamannya, dan menerbitkan Persdelict Semaoen, hasil persidangan perkaranya oleh pengadilan kolonial, sebagai bahan pendidikan politik.
Semaoen dan Darsono | foto: istimewa
Dalam kurun ini pula tokoh-tokoh sosialis Eropa, seperti Karl Marx, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Vladimir Ilich Lenin dan Henriette Roland-Holst, diperkenalkan kepada khalayak Hindia Belanda. Jika tidak mampu menerbitkannya sebagai buku atau pamflet yang memang cukup mahal, tulisan mengenai tokoh-tokoh ini biasanya dimuat bersambung dalam suratkabar pergerakan seperti Sinar Hindia, Si Tetap, Soeara Bekelai, Halilintar Hindia, Djam, dan lain-lainnya. Peristiwa dunia yang penting juga mendapat perhatian khusus lewat penerbitan bukubuku seperti Pemogokan Besar di Shanghai dan laporan-laporan rinci mengenai Revolusi Rusia 1917.
Mas Marco Kartodikromo, yang dikenal sebagai jurnalis-aktivis terkemuka dan karena itu bolakbalik mendekam di bui, menerbitkan Babad Tanah Djawi, yang menulis sejarah kembali berdasarkan tafsir pergerakan. Alasannya menulis disebutkan, "untuk merebut kembali sejarah yang sudah terlalu lama dikuasai oleh penguasa kolonial". Sementara itu Ki Hadjar Dewantara menerjemahkan Sjair Internationale, lagu revolusioner karangan Eugene Pottier dan menerbitkannya secara terpisah dalam bentuk pamflet.
Sampai 1920-an suratkabar tetap menjadi bentuk yang paling populer, karena disamping harganya yang relatif murah, juga terbit setiap hari dan memuat berita-berita aktual. Panggung pergerakan yang penuh dengan penerbitan kritis ini melahirkan tokoh-tokoh seperti Darsono, Tjipto Mangoenkoesoemo, Musso, Tan Malaka dan Alimin. Organisasi rakyat berhaluan kiri memang unsur yang paling aktif, dengan tokoh-tokoh seperti S. Goenawan yang menjadi distributor buku-buku pergerakan di Bandung. Tapi ada juga tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang aktif menulis dan mengedarkan terbitan kiri seperti Haji Fachroeddin dan Haji Misbach di Jawa Tengah. Dari segi tirasnya penerbit pergerakan ini jauh melampaui kemampuan penguasa kolonial. Seperti Si Tetap yang diterbitkan VSTP (Serikat Buruh Kereta Api dan Tram) Semarang bisa mencapai tiras 15.000 eksemplar, sementara majalah andalan Balai Poestaka, Pandji Poestaka, yang juga diterbitkan dalam bahasa Melayu, hanya bisa mencapai 1.500 eksemplar pada tahun yang sama.
Pada 1925 seorang pegawai kecil bernama Partondo menerjemahkan Manifesto Komunis dari bahasa Belanda dan memuatnya secara bersambung di harian Soeara Ra'jat. Pada tahun yang sama terjemahan itu dicetak dalam bentuk pamflet oleh percetakan serikat buruh kereta api di Semarang dengan pengantar dari Axan Zain alias Soebakat. Pamflet itu menjadi satu-satunya karya Marx yang pernah diterbitkan dalam bahasa Melayu sebelum kemerdekaan.
Maraknya buku-buku pergerakan tentu mengundang reaksi penguasa kolonial. Berulangkali para tokoh pergerakan dijerat dengan pasal-pasal hukum pidana dan diseret ke bui, seringkali selama bertahun-tahun. Percetakan milik pemodal Belanda pun akhirnya menolak mencetak buku-buku pergerakan, terutama setelah terjadinya pemogokan besar di percetakan Van Dorp, Semarang, pada 1920. Penguasa kolonial mendukung tindakan Van Dorp dengan menyita bukubuku pergerakan dan menutup toko-toko yang menjualnya. Pukulan paling telak terjadi pada 1926-27 setelah pemberontakan nasional di Jawa dan Silungkang, Sumatera Barat. Belasan orang dihukum mati di depan umum, sementara sekitar 13.000 orang dibuang ke Boven Digoel, termasuk tokoh-tokoh penerbit pergerakan, seperti Mas Marco Kartodikromo dan Ali Archam, yang kemudian meninggal di pengasingan.
Mas Marco dan istri dibuang ke Digul | foto: KITLV
Setelah itu penerbitan buku pergerakan dengan tema-tema yang menentang kolonialisme, kapitalisme dan membawa bendera pembebasan rakyat, hanya diedarkan secara terbatas. Baru pada 1950-an penerbitan seperti itu kembali hidup, terutama dengan berdirinya (kembali) Partai Komunis Indonesia. Untuk keperluan pendidikan kadernya, PKI menerjemahkan beberapa buku seperti Dasar-Dasar Leninisme karya Stalin dan Tentang Partai oleh Liu Shao-Chi. Karya klasik Lenin seperti Imperialisme, Tahap Tertinggi Kapitalisme dan Negara dan Revolusi juga mendapat giliran pertama, di samping karya Marxis Belanda J. Rutgers, Indonesia.
Suratkabar kembali menjadi bentuk yang paling disukai untuk mengedarkan ide-ide kiri dan kritis. Harian Rakjat mulai diterbitkan pada Juli 1951 dengan tiras 2.000 eksemplar dan dalam waktu dua tahun sudah melonjak menjadi 12.500 eksemplar. Pada 1956 suratkabar itu dengan tiras 55.000 mengungguli penerbitan lain seperti Pedoman dari PSI dengan 40.000 eksemplar atau Abadi dari Masjumi dengan 34.000 eksemplar. PKI juga menerbitkan bulanan dalam bahasa Inggris, Monthly Review, yang pada 1954 diubah menjadi Review of Indonesia.
Pada 1950-an diperkirakan setiap tahun PKI menerbitkan sekitar 700.000 eksemplar buku. Catatan lain mengatakan pada 1958 partai itu menerbitkan 70 judul buku dalam setahun dan menguasai 50 terbitan berkala. Bukan hanya buku-buku politik dan analisis ekonomi yang menarik perhatiannya, tapi juga karya-karya sastra Maxim Gorky, Julius Fucik, Sholokov dan Ilya Ehrenburg. Namun keliru jika menganggap penerbitan buku-buku dalam tradisi Marxis dimonopoli sepenuhnya oleh PKI. Misalnya Jajasan Pembangunan yang dekat dengan PSI beberapa kali menerbitkan buku semacam itu, seperti Marxisme karya Henri Lefebvre. Sementara penerbit umum juga banyak mengeluarkan terjemahan buku-buku tentang perjuangan rakyat Kuba dan Tiongkok karena menganggapnya sebagai sumber inspirasi antikolonial. Menurut sebagian tokoh di zaman itu, buku-buku tentang perjuangan revolusioner di negeri lain - terutama yang dikisahkan secara romantis - selalu laku keras dibandingkan buku teori atau analisis politik dan sejarah yang kering.
Tragedi berdarah 1965 mengubah segalanya. Militer mengambil alih kekuasaan dan ideologi kiri - termasuk buku-buku dan penerbitan lainnya - dianggap sebagai bahaya yang merusak, karena itu patut dimusnahkan. Ratusan ribu bahan bacaan disita dari para pemilik maupun yang masih tersimpan di gudang dan percetakan, lalu dibakar di hadapan umum. Anehnya sebagian mahasiswa dan intelektual juga ikut merayakannya sebagai 'saat kebebasan', dan turut membakar buku-buku dan segala dokumen yang mereka anggap 'beracun'.
Sikap anti-peradaban ini terus diperlihatkan selama masa kekuasaan Orde Baru. Di Yogyakarta buku-buku yang dianggap berkaitan dengan PKI - termasuk buku apa pun dalam aksara Tionghoa - ditempatkan di balik terali yang dikunci dengan gembok besar. Jaksa Agung pun menjadi penguasa tertinggi untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibaca oleh khalayak ramai. Dan di dalam daftarnya kita temukan sebuah novel dari abad ke-19 karya Haji Mukti Ali yang disunting oleh Pramoedya Ananta Toer, sebagai 'buku terlarang'. Sementara Perpustakaan Nasional RI untuk waktu cukup lama menganggap novel Atheis dari Achdiat K. Mihardja sebagai buku yang tidak pantas dibaca begitu saja oleh umum, sehingga memasukkannya dalam daftar buku yang hanya boleh dibaca dengan izin Bakorstanas.
Buku-buku terlarang di balik terali | foto: Etnoreplika
Memang tidak ada pikiran yang dapat dihapus sepenuhnya dari benak kolektif. Pada 1980-an beberapa intelektual seperti Adi Sasono dan Dawam Rahardjo mulai kembali membicarakan Marxisme, lewat teori ketergantungan yang bersumber pada tradisi pemikiran radikal Amerika Latin, dalam berbagai penerbitan. Di rumah-rumah kos fotokopi 'buku lama' termasuk yang paling disukai mahasiswa, begitu pula dengan buku-buku berbahasa Inggris tentang Marx, revolusi, kapitalisme dan sebagainya. Bisa saja orang menyebut maraknya 'buku kiri' di Indonesia belakangan ini cuma sekadar trend saja. Yang pasti buku tentang penindasan dan pembebasan tetap akan bermunculan selama penindasan masih ada dan pembebasan belum tercapai.
Tim Media Kerja Budaya: Ayu Ratih, Hilmar Farid, Razif
sumber: Media Kerjabudaya (MKB) edisi04/2000
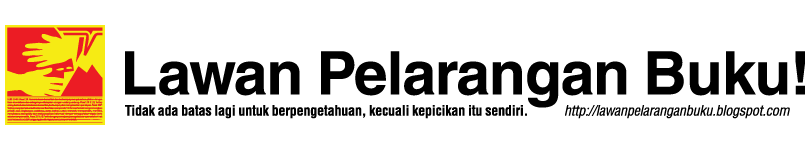
Tidak ada komentar:
Posting Komentar